Oleh: Agung Hermansyah
(Peneliti Muda Law Action (LawAct) Indonesia dan Mahasiswa Jurusan Hukum Agraria dan SDA Fakultas Hukum Unand)
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang paling berharga di bumi ini. Hutan memiliki berbagai fungsi dan manfaat untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Hutan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup karena hutan dalam rantai makanan berperan sebagai produsen. Selain itu, Hutan juga merupakan ''paru-paru dunia'' karena menghasilkan oksigen (O2) yang diperlukan untuk bernafas. Tak hanya itu, hutan juga berperan penting dalam menjaga temperatur suhu bumi dan mereduksi panas sinar matahari yang berbahaya bagi makhluk hidup di bumi.
Namun, peran dan fungsi hutan tersebut kian hari semakin terancam. Hal ini disebabkan karena tingginya laju kerusakan hutan. Selama kurun waktu 15 tahun, kerusakan hutan didunia mencapai 148 juta hektare. Indonesia menempati urutan kedua dunia kerusakan hutan. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI) hutan Indonesia berkurang secara drastis dalam kurun waktu 2009-2013, Indonesia kehilangan 4,6 juta hektar hutan. EG Togu Manurung ketua FWI mengatakan setiap menit, hutan seluas 3 lapangan bola hilang (Kompas, 11/12/2014).
Laju kerusakan hutan yang tinggi disebabkan oleh aktivitas penebangan liar (ilegal loging), pembakaran hutan, dan perusakan hutan yang bermuara pada tindakan perusakan lingkungan. Kerusakan hutan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan. Kayu-kayu yang ditebang secara ilegal telah membuat flora dan fauna mati. Hutan yang dibakar membuat tanah tandus dan mendatangkan bencana kabut asap. Perusakan hutan telah merubah bentuk fisik alam.
Faktor penyebab laju kerusakan hutan tidak bisa dilepaskan dari persoalan korupsi disektor kehutanan (forest corruption). Pihak berwenang menerima uang untuk memudahkan perizinan. Korupsi memicu masalah tumpang tindih perizinan dan pembukaan hutan untuk kepentingan komersial.
Aliran uang berupa suap, gratifikasi dan fee, atau sebagainya seringkali terjadi antara pejabat negara dengan perusahaan (korporasi). Korporasi mendapatkan lahan karena menyuap pejabat dalam memudahkan proses pengeluaran izin konsesi operasional suatu perusahaan. Hutan-hutan disewakan kepada pihak korporasi berupa hak pengelolaan hutan (HPH) yang secara operasional tidak dipergunakan untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, tetapi hanya menambang kayu (timber mining) secara berlebihan. Celakanya lagi, semenjak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan (UUPK) menjadi langkah awal dimulainya ''pengaplingan'' wilayah kehutanan secara besar-besaran oleh pengusaha kelas kakap.
Praktik korupsi kehutanan merupakan tindakan kriminal yang tak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Korupsi kehutanan adalah bentuk pengekangan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih. Selain itu, korupsi kehutanan juga mendatangkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kabut asap yang membuat masyarakat dipaksa mengalami sakit atau dipaksa menghirup kabut asap beracun dari hasil oksidasi pembakaran hutan yang berujung pada kematian.
Subtansi Hukum
Untuk mencegah bencana alam yang lebih besar lagi akibat korupsi kehutanan, maka menjaga kelestarian hutan beserta fungsi ekologisnya merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Wujud dari penjagaan tersebut adalah dengan melakukan penegakkan hukum secara responsif.
Ditinjau dari subtansi hukum, ada beberapa produk hukum yang bisa digunakan dalam menjerat perbuatan melawan hukum (onrechtmatgedaad) disektor kehutanan, yakni UU No. 41 tahun 1999 (UU Kehutanan), UU No. 32 tahun 2009 (UU Lingkungan Hidup/UUPPLH), dan UU No. 18 tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan/UUP3H).
Di dalam UU kehutanan pengaturan tentang upaya dalam menanggulangi kejahatan kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU kehutanan. Upaya itu berupa hak untuk mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke pengadilan atau melaporkan ke aparat penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU kehutanan hanya bisa menjerat pelaku kejahatan kehutanan secara administrasi dan atau perdata. Sehingga penyelewengan terhadap pengelolaan hutan tidak bisa dijerat dengan pidana karena UU kehutanan sendiri tidak mengatur hal tersebut.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) UU kehutanan pada frasa ''terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku''. Artinya, subjek yang bisa digugat adalah subjek yang kegiatan mengeksploitasi hutan tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan. Tuntutan dalam hal ini yakni meminta ganti kerugian bila merugikan kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, UU kehutanan tidak punya ketentuan Pasal khusus yang menjelaskan hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan kehutanan.
Kemudian UUPPLH digunakan apabila telah terjadi kerusakan lingkungan atau pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL. Secara normatif, UUPPLH ini sama dengan UU kehutanan. Tapi, UUPPLH memberi peluang untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UUPPLH. Hanya saja dalam tataran implementasi penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat sulit direalisasikan. Hal ini dikarenakan terkait dengan masalah pembuktian yang harus memuat unsur kesalahan (fault), kelalaian (negligence), ketidak-hati-hatian (caraless), kesengajaan (intentionality), unsur melawan hukum (tort), ataupun kerusakan (damages). Masalah beban pembuktian (burden of proof) tersebut tidaklah mudah, terutama berkaitan dengan pembuktian ilmiah (M. Daud Silalahi, 2006). Seyogyanya baik UUPPLH maupun UU kehutanan tidak bisa menjerat dan mengendus praktik korupsi (KKN) dalam pengeluaran izin kehutanan.
UUP3H menjadi babak baru dalam memerangi praktik korupsi kehutanan (forest corruption) semenjak diundangkan pada 6 Agustus 2013 lalu. Ketentuan dalam UUP3H menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan. Penyelewengan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun hasilnya yang menjurus kepada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 28 UUP3H (untuk pejabat). Sanksi pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap Pasal 19 UUP3H bagi orang perseorangan di pidana penjara paling lama 15 tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 100 miliar dan untuk korporasi dapat di pidana penjara paling lama seumur hidup serta pidana denda Rp. 1 triliyun sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 UUP3H.
Lalu, bagi para pejabat yang kongkalikong dengan para pelaku usaha terkait persoalan perizinan yang dikategorikan terhadap pelanggaran Pasal 28 UUP3H dapat di pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda Rp. 10 milyar sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 UUP3H. Tak tanggung-tangung, UUP3H juga menambahkan pidananya 1/3 dari ancaman pidana pokok bagi pejabat yang terlibat dalam kegiatan pembalakkan liar.
Menurut hemat saya, dalam memberantas praktik korupsi kehutanan yang dilakukan oleh mafia kehutanan melalui pengeluaran perizinan, UUP3H lebih cocok diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi kehutanan ketimbang UU kehutanan ataupun UUPPLH. Penjatuhan sanksi pidana dalam UUP3H tidak menitikberatkan pada beban pembuktian sebagaimana UUPPLH. Misalnya Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait (Pasal 33 UUP3H).
Selain itu, UUP3H juga memberikan perlindungan khusus bagi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya mencegah dan memberantas perusakan hutan. Perlindungan hukum yang diberikan dan dijamin oleh UUP3H sebagaiman tercantum dalam Pasal 77 dan 78 yakni berupa perlindungan pribadi, keluarga dan harta kekayaan serta tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dengan catatan beritikad baik.
Jika subtansi hukum dalam UUP3H sangat memadai untuk menjerat pelaku korupsi kehutanan, maka juga harus diiringi dengan penegakkan hukum yang baik oleh aparatur hukum. Namun nyatanya penegakkan hukum disektor kehutanan dan lingkungan hidup sering terganjal karena masalah minimnya apartur yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah tersebut, mendorong sinergitas antarlini adalah solusinya.
Pada tahap penyidikan dan penuntutan perlu dibuat tim khusus yang terdiri dari unsur Polisi Hutan, PPNS yang ditunjuk oleh menteri kehutanan dan lingkungan hidup, serta kejaksaan. Sedangkan pada tahap persidangan jika tidak memiliki hakim yang berkompetensi dalam bidang kehutanan, maka Mahkamah Agung berhak mengangkat hakim ad hoc untuk memeriksa perkara perusakan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UUP3H. Langkah ini selain menutupi kekurangan SDM dibidang tersebut, juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sehingga pelaku korupsi kehutanan tidak bisa lepas dari sanksi pidana.****
Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau
























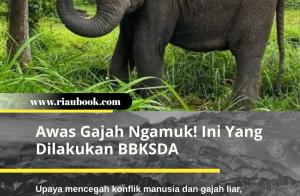

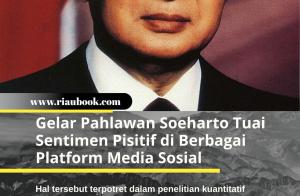

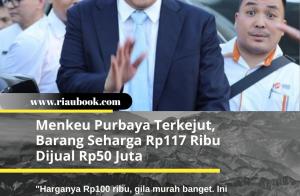
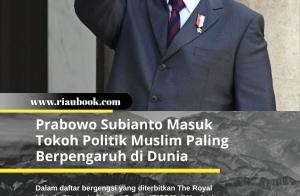














Golkar Riau Akan Dipimpin Seorang Pejuang, Bukan Petarung
Goresan; Nofri Andri Yulan, S.Pi (Generasi Muda Partai Golkar)1. PI (Parisman Ikhwan) didukung penuh oleh Ketua DPD I Partai Golkar…